Cerpen Agus Noor
Dimuat di Koran Tempo (03/29/2009)
Ambulans yang Lewat Tengah Malam
Ambulans yang membawa jenazahmu berkali-kali oleng karena sopirnya ngantuk. “Aku tak mau mati kecelakaan lagi,” katamu. “Sini, biar saya setir.” Pak Sopir pun gantian istirahat di peti mati. Kulihat ambulans itu melintas pelan menuju rumahmu.
Sirene
Kelak, sejak kematianmu itu, anak-anak di kampung kami selalu ketakutan bila mendengar sirene. Bila ada anak yang rewel, si ibu akan menakut-nakuti, “Nanti kau diculik ambulans….” Setiap ada sirene melintas, anak-anak yang tengah bermain gobag sodor atau petak umpet buru-buru berlarian masuk rumah. “Mereka selalu ngeri membayangkan ambulans yang disetiri mayatmu,” kataku.
Kau tersenyum mendengar kisah itu.
Kucing Hitam
Aku ingat, saat para tetangga datang melayat. Banyak yang penasaran kenapa kau mati begitu mendadak. Mereka bercakap nyaris berbisik, menduga-duga–mungkin ada juga yang diam-diam menggunjingkanmu–sementara jenazahmu berbaring tenang. Bau kematian seperti mengendap dalam ruangan.
Saat itulah, mendadak, seseorang menjerit, ketika melihat seekor kucing hitam melompati jenazahmu. Beberapa pelayat yakin: saat itu mereka melihat matamu berkedip-kedip.
Kasus Salah Tangkap
Sampai kini, kematianmu masih berupa misteri bagi kami.
Beberapa orang meyakini, hari itu kau diciduk polisi. Kau tak pernah bisa mengerti, kenapa polisi menangkapmu. Mereka terus menginterogasi. Menggertak dan memukulmu berkali-kali. Memaksamu agar mengaku. Kau dituduh membunuh istrimu. Padahal istrimu masih hidup. Kaulah yang mati.
Misteri Mutilasi
Tetapi beberapa orang yang lain bilang, kalau kau sesungguhnya mati bunuh diri. “Kuperhatikan ia tampak murung belakangan ini,” seseorang berkata. “Aku yakin ia memotong-motong tubuhnya sendiri, dan untuk menghilangkan jejak, ia segera membuangnya ke pinggir kali.”
Itulah sebabnya, kata orang itu melanjutkan, polisi masih sibuk mencari pembunuhnya, sampai kini!
Tentang Seorang Perempuan
Seminggu setelah pemakamanmu, seorang perempuan muncul di kampung kami. Ia menggendong bayi mungil. Wajahnya gugup dan pucat, tetapi tak menghapus kecantikannya. Seolah takut ketahuan, perempuan itu menanyakan di mana rumahmu. Sikapnya membuat kami curiga: jangan-jangan ia istri kedua atau simpananmu.
Lalu seorang warga menjelaskan, kalau kau sudah mati.
“Mati?” ia terlihat tak percaya. “Barusan tadi pagi aku bertemu dengannya….”
Cerita Pelayan Kafe
Seorang tetangga, yang bekerja sebagai pelayan kafe, satu malam menemuiku. Ia bilang, ia juga barusan melihatmu.
Ia melihatmu duduk di sudut remang kafe tempatnya bekerja. Memesan minuman ringan dan kentang goreng. “Katanya ia janjian mau ketemu dengan sampeyan.”
Tapi semalaman aku lembur di kantor, tegasku.
“Ya, ia memang terus sendirian, tapi seolah bercakap-cakap dengan sampeyan yang tak pernah datang.” Sampai kafe tutup. Namun para pelayan kafe masih melihatnya terus duduk di kursi itu. “Sebelum aku pulang, ia menitipkan ini padaku.” Ia menyodorkan sekeping koin. Dan aku segera mengenalinya.
Pada Sebuah Kuburan
Dulu, semasa kanak, kita menemukan sekeping koin perak kusam di pekuburan. Kita memang sering keluyuran ke pekuburan selatan kampung itu. Orang-orang bilang kuburan itu berhantu. Sering, bila tengah malam, terdengar suara yang terus melolong. Aku selalu ketakutan. Seperti kudengar suara lolong menyayat orang sekarat. Tapi kau malah cekikikan.
“Kelak,” katamu, “aku akan mati menjerit kesakitan seperti itu. Aku akan mati terpotong-potong, dan dibuang ke kuburan ini….”
Kemenyan
Barangkali kamu memang tak pernah mati.
Para peronda sering melihatmu berkelebat pulang malam-malam. Mereka kadang juga samar-samar melihatmu duduk-duduk di beranda rumahmu–sesekali batuk-batuk kecil atau berdehem–sembari menikmati rokok kretek. Tapi para peronda itu mencium aroma kemenyan merebak di udara yang seketika terasa menjadi lembab.
Para peronda juga sering melihat istrimu tengah malam berdiri di pintu menunggumu.
Seusai Pemakaman
Aku jadi ingat pada sore seusai pemakaman. Para pelayat baru saja menguburkanmu. Saat itu aku melintas depan rumahmu, dan kulihat kau seperti baru saja pulang. “Ayah pulang! Ayah pulang!” anak-anakmu berlarian riang menyambutmu. Bergelayutan manja pada lenganmu.
Di pintu, kusaksikan mata istrimu berlinang.
Koin Hitam
Kupandangi koin perak yang telah menghitam itu. Tergeletak di meja. Kau tahu, sejak dulu aku tak mau keping koin itu. Tapi tiap kali aku datang ke rumahmu hendak mengembalikan koin itu, yang ada hanya istrimu. Senyumnya yang manis menyuruhku masuk, matanya yang gelisah melirik ke halaman, takut ada yang memergoki.
Setelah kau mati, aku pun sudah berusaha membuang jauh-jauh koin itu berkali-kali. Membuangnya ke selokan. Membuangnya ke tempat sampah. Bahkan sampai jauh ke luar kota. Tapi koin itu selalu saja kembali. Begitu saja: tiba-tiba sudah tergeletak di meja.
Kapak
Aku mengingat malam itu sebagai malam mengerikan dalam hidupku. Kau muncul dan berkata, “Kau punya kapak?”
Apakah kau akan membelah kayu malam-malam begini?
Lalu kau bercerita. “Ada ular dalam kepala istriku. Ular itu datang setiap kali aku tak ada, menyelusup lewat telinga, dan kini mendekam dalam kepalanya. Mungkin kapak ini ada gunanya….”
Tukang Ramal
Kita belum lagi genap tiga belas tahun ketika datang ke pasar malam itu. Keramaian dan lampu warna-warni seperti mimpi yang ganjil. Aku pingin gulali, tapi kau mengajakku ke tukang ramal bermata juling. Kau ingin tahu, bagaimana nanti kita mati.
Tukang ramal itu menyeringai menatap kita “Kalian memang sahabat yang luar biasa,” katanya, “karena kalian mencintai perempuan yang sama.” Kita masih saling bertatapan, ketika tukang ramal itu menarik tanganku. “Dan kau, kau akan mati karena tabrak lari.”
Alibi
Cerita ini kudengar dari para tetangga, karena saat itu aku memang sudah menjauh dari hidupmu.
Mereka mendengar suara istrimu menjerit kesakitan. Itulah jerit kematian paling mengerikan. Pagi harinya, mereka menemukan istrimu mati dengan kepala pecah. Kapak itu tak pernah ditemukan. Meski para tetangga curiga, polisi tak bisa mendakwamu, karena saat itu kau tak ada di tempat kejadian. Kau juga sedang berada di tempat lain, ketika ketiga anakmu ditemukan mati mengenaskan.
Dan para tetangga yang keheranan kemudian mengatakan: ketika mayatmu ditemukan, polisi pun tak bisa mendakwamu. Karena kau juga tak ada di tempat kejadian.
Saat itu kupikir mereka terlalu melebih-lebihkan.
Anjing
Kawan-kawan sepermainan sering bilang, kita pasangan serasi. Mereka tak tahu kalau kau tak menyukaiku yang pendiam. “Kau terlihat mengerikan bila sedang diam,” katamu selalu. “Seperti ada seorang pembunuh yang diam-diam sedang menguasai tubuhmu.”
Suatu hari kau marah karena nyaris digigit anjing tetanggamu. Aku hanya diam mendengar ceritamu. Dua hari kemudian kau mendapati anjing itu mati digorok dan digantung di pagar rumah tetanggamu.
Teka-teki Wajah Pembunuh
Inilah permainan yang kita sukai, menebak teka-teki: bila kelak kita mati terbunuh, seperti apakah wajah pembunuh itu? Kemudian kita masing-masing mengambil kertas dan pensil, membayangkan wajah itu, dan menggambarnya.
Kita melipat kertas itu setelah selesai. Memasukkannya ke amplop, lantas membakarnya, agar kita bisa terus penasaran dan menebak-nebak wajah siapakah yang kau gambar dan aku gambar. Menyimpan rahasia memang selalu mendebarkan.
“Aku bisa menduga, wajah siapa yang kau gambar,” katamu, sambil memandangi api yang melahap kertas itu.
Kubayangkan wajah itu hangus dalam api.
Sumur Tua di Belakang Rumah
Ada sumur tua di belakang rumah kakekmu. Konon, airnya selalu berwarna merah setiap purnama. Di jaman Gestapu dulu, kakekmu dibantai dan dilempar ke sumur itu. Sejak itu, siapa pun tak berani mendekat.
Tapi diam-diam kita suka ke sana, menjenguk ke dalamnya, berharap menyaksikan mayat kakekmu mengapung. Airnya memang begitu bening. Yang kita lihat justru bayangan mayat kita sendiri: memar, rusak dan berdarah karena kecelakaan. Meringkuk di dasar sumur itu.
Puisi Cinta Semasa Remaja
Kau tahu aku suka puisi. Karena itu, ketika kau jatuh cinta, kau memintaku menulis puisi. Kau sebut nama gadis yang telah membuatmu jatuh cinta. Aku pun segera tahu: itulah puisi paling bagus yang bakal berhasil aku tulis.
Kau senang sekali dengan puisi itu. “Kamu benar-benar bisa melukiskan seluruh perasaanku,” katamu. Tidak, aku tak menuliskan perasaanmu, jawabku. Dalam diam tentu saja.
Mayat dalam Koper
Setelah kau menikah, aku memilih pergi mengembara. Ketika tak ada kabar, kau sering membayangkanku sudah mati. Kemudian dari para tetangga aku mendengar, bila sedang ronda kau suka cerita, kalau aku tak lain psikopat yang dicari-cari polisi. “Suatu hari psikopat itu memotong-motong tubuhnya sendiri. Dan sebelum polisi tiba, ia bergegas mengemas koper yang berisi potongan tubuhnya sendiri.”
Mereka selalu tertawa mendengar cerita itu.
Tabrak Lari
Lalu hari sebagaimana diramalkan itu tiba.
Saat terburu berangkat kantor kau menabrak pejalan kaki. Tubuhnya terpelanting dan tergilas. Kau terus tancap gas. Malam harinya, istrimu begitu sedih setelah mendapat kabar kamu mati tertabrak ambulans yang langsung melarikan diri. Ambulans hantu, kata orang-orang. Ambulans yang disetiri mayat yang dibawanya.
Kau menangis menceritakan semua kisah ini padaku yang tadi pagi mati karena tabrak lari. ***
Jakarta, 2009
 Di depan Akademi Jakarta pada 20 Desember 2006,
Di depan Akademi Jakarta pada 20 Desember 2006,  Dalam konteks ini, ada baiknya kita bercermin dari Goenawan Mohamad dalam merespons polemik yang seolah-olah mempertentangkan antara kebebasan berkarya dan standar-standar moralitas itu.
Dalam konteks ini, ada baiknya kita bercermin dari Goenawan Mohamad dalam merespons polemik yang seolah-olah mempertentangkan antara kebebasan berkarya dan standar-standar moralitas itu. 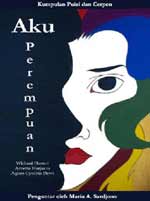 Persoalannya, hidup di tengah-tengah zaman yang kian menghamba pada selera kaum kapitalis ini tidaklah mudah untuk menerbitkan antologi sastra. Untung-rugi selalu menjadi pertimbangan utama. Sebuah penerbit biasanya tidak akan berbuat konyol dengan menerbitkan buku-buku sastra (termasuk antologi) kalau akhirnya buku-buku tersebut “mati” di pasaran.
Persoalannya, hidup di tengah-tengah zaman yang kian menghamba pada selera kaum kapitalis ini tidaklah mudah untuk menerbitkan antologi sastra. Untung-rugi selalu menjadi pertimbangan utama. Sebuah penerbit biasanya tidak akan berbuat konyol dengan menerbitkan buku-buku sastra (termasuk antologi) kalau akhirnya buku-buku tersebut “mati” di pasaran.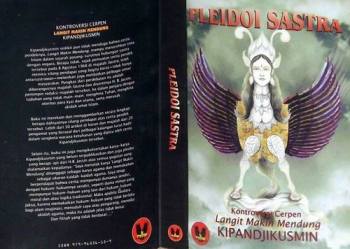 Tak banyak yang tahu siapa sesungguhnya Kipandjikusmin itu. Ada yang menduga –melihat kegigihan H.B. Jassin dalam membela LMM dan Kipandjikusmin di pengadilan– Kipandjikusmin adalah pseudonim H.B. Jassin sendiri. Namun,
Tak banyak yang tahu siapa sesungguhnya Kipandjikusmin itu. Ada yang menduga –melihat kegigihan H.B. Jassin dalam membela LMM dan Kipandjikusmin di pengadilan– Kipandjikusmin adalah pseudonim H.B. Jassin sendiri. Namun,  Sejujurnya, saya tersentak ketika membaca komentar Bu Amanda terhadap cerpen saya “Sang Pembunuh”. Mohon maaf sebelumnya kepada Bu Amanda kalau komentar Ibu saya jadikan sebagai topik tulisan. Hal ini penting lantaran menyangkut kreativitas dan “keliaran” imajinasi saya yang sedang belajar menulis cerpen. Apalagi, cerpen tersebut dinilai oleh Bu Amanda “tidak mungkin murni dari bayangan atau ide kreatifitas semata tanpa ditunjang beberapa fakta-fakta yang nyata. Kenapa? Karena cerita tersebut sarat dengan elemen-elemen fakta nyata yang hanya bisa diketahui dan diresapi oleh seseorang yang memang benar-benar telah melalui sebuah masa dibalik jeruji besi.” *Aduh, garuk-garuk kepala.*
Sejujurnya, saya tersentak ketika membaca komentar Bu Amanda terhadap cerpen saya “Sang Pembunuh”. Mohon maaf sebelumnya kepada Bu Amanda kalau komentar Ibu saya jadikan sebagai topik tulisan. Hal ini penting lantaran menyangkut kreativitas dan “keliaran” imajinasi saya yang sedang belajar menulis cerpen. Apalagi, cerpen tersebut dinilai oleh Bu Amanda “tidak mungkin murni dari bayangan atau ide kreatifitas semata tanpa ditunjang beberapa fakta-fakta yang nyata. Kenapa? Karena cerita tersebut sarat dengan elemen-elemen fakta nyata yang hanya bisa diketahui dan diresapi oleh seseorang yang memang benar-benar telah melalui sebuah masa dibalik jeruji besi.” *Aduh, garuk-garuk kepala.*